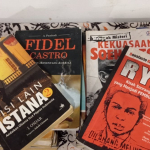Dengarkan artikel ini:
Di tengah sorotan terhadap kiai dan pondok pesantren, ketegangan antara nilai tradisional di daerah dan modernitas urban makin terasa. Apakah ini soal ketidaklayakan atau persoalan Jakarta-sentrisme di Indonesia?
“Pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan agama, tetapi pusat pembentukan moral, karakter, dan kemanusiaan. Mari bersama menjaga marwahnya” – Nasaruddin Umar, Menteri Agama (15/10/2025)
Cupin menatap layar ponselnya sambil mengerutkan dahi. Di beranda media sosialnya, video tentang santri-santri di Kediri yang sedang membantu pembangunan gedung pesantren sedang viral. Kolom komentarnya ramai, ada yang memuji dan ada pula yang menuduh eksploitasi. “Lucu juga,” gumamnya, “orang-orang kota sibuk berdebat soal tradisi yang mungkin tidak pernah mereka alami.”
Beberapa bulan terakhir, dunia pesantren memang menjadi sorotan publik. Mulai dari tragedi ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo hingga perdebatan tentang penghormatan terhadap kiai. Insiden di Sidoarjo memicu keprihatinan besar. Banyak yang mempertanyakan bagaimana lembaga pendidikan yang sudah berdiri puluhan tahun masih menghadapi masalah keamanan dasar. Tragedi itu menjadi simbol rapuhnya sistem pengawasan terhadap lembaga pendidikan tradisional di Indonesia.
Cupin membaca komentar salah satu netizen yang berkata, “Kalau saja pesantren dikelola seperti sekolah modern di Jakarta, pasti aman.” Kalimat itu membuatnya berpikir. Mengapa ukuran modern selalu diambil dari Jakarta? Tidak lama setelah itu, muncul video viral dari Lirboyo yang menampilkan santri membantu membangun gedung pesantren. Sebagian warganet menuduh hal itu sebagai bentuk eksploitasi tenaga kerja anak, sementara yang lain membelanya sebagai bagian dari pendidikan karakter. Dua pandangan nilai yang sama-sama baik akhirnya bertemu dalam ketegangan yang sulit dijembatani.
Bagi masyarakat pesantren, kerja seperti itu bukan hal baru. Sejak lama, para santri memang dididik untuk hidup sederhana, mandiri, dan berkontribusi langsung pada lingkungan mereka. Namun bagi masyarakat urban yang terbiasa dengan regulasi ketat soal hak anak dan tenaga kerja, hal itu tampak janggal. Dua sistem nilai yang berbeda akhirnya saling berbenturan di ruang digital.
Kontroversi lain muncul ketika beberapa video memperlihatkan santri mencium tangan dan berjalan membungkuk di hadapan kiai. Sebagian warganet menilai tindakan itu feodal dan tidak sesuai dengan semangat kesetaraan zaman modern. Tetapi bagi masyarakat pesantren, itu adalah bentuk adab. Cupin tersenyum melihat komentar-komentar yang menyebut tindakan itu sebagai kultus individu. “Mereka tidak tahu,” katanya pelan, “bahwa mencium tangan bukan bentuk tunduk, melainkan simbol cinta dan keberkahan.”
Kritik dari publik urban membuka pertanyaan yang lebih besar. Apakah kritik-kritik itu lahir dari kepedulian terhadap nilai kemanusiaan, atau justru merupakan cerminan bias kultural yang Jakarta-sentris? Dan mungkinkah tradisi pesantren bisa dilihat secara adil tanpa kacamata nilai-nilai kota besar?
Kiai dan Pesantren dalam Sorot?
Cupin mulai mencari jawabannya. Ia membuka beberapa buku antropologi dan teori budaya yang membahas perbedaan antara masyarakat rural dan urban. Salah satu istilah yang menarik perhatiannya adalah power distance atau jarak kekuasaan sosial. Konsep ini dikembangkan oleh Geert Hofstede dalam bukunya Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations. Menurut Hofstede, masyarakat dengan power distance tinggi cenderung menerima hierarki sosial sebagai sesuatu yang wajar. Indonesia termasuk di dalamnya.
Di desa-desa Jawa Timur, tempat banyak pesantren besar berdiri, struktur sosial hierarkis masih kuat. Kiai bukan hanya guru agama, tetapi juga tokoh moral, spiritual, bahkan sosial-politik. Hubungan antara kiai dan santri tidak dibangun di atas kontrak formal, melainkan pada adab dan keyakinan akan keberkahan ilmu. Dalam budaya Jawa klasik, ada konsep “guru, ratu, wong tua” yang menempatkan guru sejajar dengan orang tua dan raja. Dalam tatanan nilai seperti ini, mencium tangan guru adalah simbol penghormatan terhadap sumber pengetahuan.
Cupin teringat kisah ayahnya yang dulu mondok di Jombang. “Kalau dulu kami mencium tangan kiai,” kata ayahnya, “itu bukan karena takut, tapi karena ingin membawa pulang berkah dari ilmu.” Dari cerita itu, Cupin menyadari bahwa tradisi penghormatan di pesantren punya dimensi spiritual yang dalam. Nilai-nilai itu tidak bisa dinilai dengan kacamata rasional modern yang menuntut kesetaraan mutlak.
Sebaliknya, masyarakat urban seperti Jakarta hidup dengan nilai yang lebih egaliter. Modernisasi, pendidikan tinggi, dan paparan budaya global membentuk cara pandang yang rasional dan meritokratis. Di kota, otoritas seseorang diukur dari kemampuan dan prestasi, bukan dari posisi spiritual. Dalam dunia seperti ini, gestur fisik penghormatan terasa tidak relevan. Cupin tersenyum membayangkan reaksi seorang eksekutif muda Jakarta jika diminta mencium tangan atasannya.
Fons Trompenaars dan Charles Hampden-Turner dalam Riding the Waves of Culture membedakan masyarakat universalis dan partikularis. Masyarakat universalis, yang biasanya berkembang di kota, berpegang pada standar moral seragam untuk semua. Sementara masyarakat partikularis, seperti di pesantren, menyesuaikan nilai dengan konteks hubungan sosial. Dalam sistem partikularis, memperlakukan kiai secara istimewa tidak dianggap salah, melainkan bentuk pengakuan terhadap posisi dan tanggung jawabnya dalam komunitas.
Edward T. Hall dalam Beyond Culture menambahkan kerangka yang menarik. Ia membedakan budaya high-context dan low-context. Budaya high-context, seperti di pesantren, mengandalkan simbol dan sejarah bersama dalam komunikasi. Sementara budaya low-context di kota menuntut kejelasan dan logika eksplisit. Ketika ritual pesantren dilihat dari kacamata low-context, makna simboliknya hilang dan tampak tidak rasional.
Cupin menutup bukunya sambil berkata, “Mungkin yang salah bukan tradisinya, tapi cara kita memahaminya.” Ia mulai memahami bahwa konflik nilai sering muncul bukan karena niat buruk, melainkan karena tabrakan antara dua cara pandang yang sama-sama sah. Maka ia pun bertanya-tanya, apakah Jakarta benar-benar memahami konteks budaya di luar dirinya? Dan bagaimana peran media, yang sebagian besar berbasis di ibu kota, dalam memperkuat kesenjangan persepsi ini?
Jakarta-sentrisme dan Kuasa Representasi
Cupin kemudian menelusuri bagaimana media memproduksi narasi tentang pesantren. Ia membaca beberapa laporan dan menyadari bahwa banyak berita ditulis dari sudut pandang yang menilai, bukan memahami. Hampir semua media besar di Indonesia berkantor pusat di Jakarta. Wajar jika nilai-nilai urban menjadi standar dalam setiap liputan. “Jakarta seperti cermin besar,” gumamnya, “yang memantulkan wajah Indonesia tapi dengan biasnya sendiri.”
John B. Thompson dalam bukunya The Media and Modernity menjelaskan bahwa media memiliki kekuatan simbolik untuk membentuk persepsi publik. Melalui kontrol atas produksi simbol, media menentukan nilai-nilai mana yang dianggap penting. Dalam konteks Indonesia, media yang berpusat di Jakarta sering menampilkan nilai-nilai urban sebagai tolok ukur kemajuan nasional. Sementara nilai daerah diposisikan sebagai tradisi yang perlu diperbaiki atau dimodernisasi.
Cupin teringat sinetron yang dulu sering ia tonton. Tokoh dari desa selalu digambarkan lugu, logatnya kental, dan sering menjadi bahan lelucon. Sementara tokoh dari Jakarta tampak modern dan berpendidikan. Kini ia sadar bahwa representasi itu bukan kebetulan, melainkan cerminan bias kultural yang menempatkan Jakarta di posisi puncak. Dalam imajinasi kolektif bangsa, Jakarta menjadi simbol kemajuan, sementara daerah dianggap tertinggal.
Stuart Hall dalam Representation: Cultural Representations and Signifying Practices menyebut bahwa media tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi juga membentuk makna. Dengan dominasi Jakarta, makna tentang modernitas pun dikonstruksi agar sesuai dengan nilai-nilai kota besar. Tradisi daerah sering digambarkan sebagai kuno dan butuh modernisasi. Representasi ini membuat masyarakat urban merasa lebih rasional, bahkan lebih benar, tanpa menyadari bahwa nilai mereka pun lahir dari konteks tertentu.
Fenomena ini juga dibahas oleh Arjun Appadurai dalam Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Ia menjelaskan bagaimana globalisasi menciptakan ketegangan antara homogenisasi dan heterogenisasi. Di Indonesia, homogenisasi itu hadir dalam bentuk Jakartanisasi, yaitu penyebaran nilai-nilai Jakarta sebagai standar nasional. Nilai-nilai daerah yang berbeda sering dianggap penghalang modernisasi, bukan sebagai bagian sah dari keragaman budaya. Cupin menggeleng pelan. “Padahal justru di situlah kekayaan Indonesia berada,” katanya.
Meski begitu, Cupin juga tidak menutup mata terhadap kritik yang muncul. Ia tahu bahwa beberapa kasus di pesantren, seperti kekerasan atau kurangnya standar keselamatan, memang nyata dan perlu dibenahi. Namun ia merasa perlu membedakan antara kritik yang tulus dan kritik yang berangkat dari superioritas kultural. Ketika media lebih senang menyoroti sisi sensasional pesantren tanpa memahami konteksnya, mereka sebenarnya memperkuat jurang pemahaman antara masyarakat urban dan rural.
Akhirnya, Cupin menulis dalam catatannya, “Masalahnya bukan antara modernitas melawan tradisi, tetapi cara kita mendefinisikan keduanya.” Indonesia selama ini terlalu sering didefinisikan dari pusat. Jakarta menjadi cermin bagi seluruh negeri, padahal banyak nilai luhur tumbuh di luar sorotan kamera. Cupin menatap langit sore Jakarta yang mulai oranye dan berbisik pelan, “Mungkinkah suatu hari nanti narasi tentang Indonesia lahir dari luar Jakarta tanpa harus kehilangan rasa hormat pada perbedaan?” (A43)