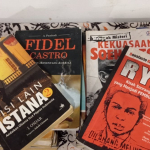Dengarkan artikel ini:
Media sosial (medsos) dihebohkan dengan pelaporan ke pihak berwajib atas pembuat dan penyebar meme yang menyertakan sosok Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. What if kalau branding Bahliln dikerjakan oleh Gen Z juga?
“Kijang satu, monitor…” – @Gerindra di X (26/6/2020)
Cupin baru saja meneguk kopi sachet keduanya ketika timeline X, dulu Twitter tapi semua orang masih nyebutnya Twitter juga, dipenuhi gambar-gambar lucu Bahlil Lahadalia. Ada yang edit fotonya seperti penyanyi dangdut, ada juga yang pakai template “Sigma Male Grindset.” Cupin ngakak, tapi nggak lama kemudian muncul kabar bahwa ada laporan polisi terkait meme itu.
“Wah, ini kayak nonton dua dunia yang nabrak,” gumam Cupin sambil garuk kepala. Dunia birokrasi yang serius bertemu dunia internet yang cair. Meme yang sejatinya jadi bahasa sehari-hari Gen Z mendadak berubah jadi barang bukti hukum.
Bahlil sendiri, sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mungkin nggak pernah nyangka dirinya bakal seviral itu di jagat maya. Meme-meme tentang dirinya tersebar ke mana-mana, dari grup receh sampai forum politik. Tapi yang bikin heboh bukan cuma lucunya meme, melainkan respons yang muncul, yaitu ada yang merasa bahwa itu bentuk penghinaan.
Fenomena ini, kalau kata Cupin, udah kayak nonton ulang film lama. Setiap kali figur publik kena banjir meme, debatnya selalu itu-itu juga: antara kebebasan berekspresi dan perlindungan nama baik. Tapi kali ini berbeda, karena yang bikin dan nyebarin meme bukan lagi aktivis digital atau buzzer politik, melainkan Gen Z. Mereka adalah generasi yang hidupnya memang sudah nggak bisa dipisahkan dari internet.
Mereka ini lahir di era di mana humor adalah cara berpikir, bukan sekadar hiburan. Meme jadi bahasa yang lebih efisien daripada paragraf panjang. Dalam satu gambar, mereka bisa menggabungkan satire, empati, dan ironi, kadang semuanya dalam satu paket.
Cupin ingat, dulu waktu mahasiswa, komunikasi politik itu bahasnya tentang framing media, pesan persuasif, dan segmentasi publik. Sekarang semuanya bisa direduksi ke satu template meme: “Gua sih yes” atau “NPC moment.” Dunia berubah cepat sekali.
Makanya, ketika meme tentang Bahlil dilaporkan ke aparat hukum, Cupin cuma bisa bilang ini bukan sekadar kasus hukum. Ini soal dua paradigma komunikasi yang tabrakan. Yang satu masih pakai aturan abad ke-20, sedangkan yang lain sudah hidup di logika abad ke-21.
Kalau dilihat dari kacamata komunikasi digital, meme itu bukan penghinaan, tapi sinyal keterlibatan. Ketika seseorang dijadikan bahan meme, artinya dia sudah masuk ke kesadaran publik. Cupin nyengir. “Kalau udah jadi meme, berarti udah jadi bagian dari budaya pop, Bro,” katanya pelan.
Nama Bahlil yang sebelumnya mungkin cuma dikenal di kalangan ekonomi dan politik kini mendadak jadi ikon internet. Ironisnya, pelaporan justru bikin meme itu makin viral. Cupin jadi ingat pepatah digital lawas, the Streisand effect. Semakin coba dikontrol, semakin liar ia menyebar.
Meme sebagai Bahasa Gen Z
Untuk memahami ini, Cupin membuka lagi catatan lama waktu dia baca buku Limor Shifman, Memes in Digital Culture. Di sana dijelaskan bahwa meme itu bukan cuma gambar lucu, tapi unit informasi budaya yang bisa berevolusi dan beradaptasi. Setiap orang yang me-remix atau share berarti ikut berpartisipasi dalam proses penyebaran makna.
“Jadi,” kata Cupin ke dirinya sendiri, “meme itu kayak DNA komunikasi zaman sekarang.”
Buat Gen Z, meme bukan sekadar bercandaan. Itu cara mereka ngobrol, menyindir, bahkan memahami dunia. Seperti yang ditulis Crystal Abidin dalam Internet Celebrity: Understanding Fame Online, meme adalah alat untuk membangun komunitas dan menegosiasikan identitas. Dalam konteks ini, ketika mereka bikin meme tentang Bahlil, mereka sedang menandai posisi mereka dalam percakapan publik. Mereka tidak hanya menonton politik, tapi ikut main di dalamnya.
Cupin membayangkan sekelompok anak muda nongkrong di kafe, buka laptop, dan mulai ngedit foto Bahlil dengan template “rizz level dewa.” Buat mereka, itu bukan penghinaan. Itu cara mereka mengekspresikan opini sekaligus bermain-main dengan simbol kekuasaan.
Yang menarik, meme itu egaliter. Semua orang bisa bikin. Kalau dulu opini publik dibentuk lewat media arus utama, sekarang siapa pun bisa ikut membangun narasi. Dalam kasus Bahlil, ribuan orang jadi co-creator dalam membentuk citra dirinya di internet. Cupin mengernyit. “Dulu yang pegang kendali itu humas kementerian, sekarang ya netizen.”
Ryan Milner dalam The World Made Meme menyebut fenomena ini sebagai participatory media culture. Di dunia seperti ini, batas antara pembuat dan penonton konten jadi kabur. Setiap orang bisa jadi komentator. Di situlah politik digital Gen Z menemukan bentuknya: informal, visual, cepat, dan spontan.
Cupin lalu nyengir waktu ingat gaya humor Gen Z yang absurd. Kadang dia butuh lima menit buat ngerti maksudnya. Meme mereka bisa berlapis-lapis makna: ejekan bisa jadi bentuk apresiasi, ironi bisa jadi tanda cinta. Di balik humor yang tampak ngawur, ada literasi visual yang tinggi.
Kalau kita pakai logika komunikasi konvensional, ya jelas gagal paham. Meme bukan teks biasa. Ia campuran konteks, timing, dan emosi kolektif. Karena itu, waktu seseorang bikin meme tentang gaya bicara Bahlil, itu bukan semata bahan ketawaan, tapi cara publik memahami figur ini dalam lanskap sosial yang lebih luas.
Cupin kemudian teringat argumen menarik: buat banyak anak muda, meme adalah cara menghadapi dunia yang terlalu rumit. Ketika ekonomi sulit, politik sumpek, dan informasi berseliweran tanpa henti, mereka merespons dengan humor. “Ketawa dulu, mikir belakangan.”
Tapi jangan salah, kata Cupin sambil menunjuk layar laptopnya, itu juga bentuk perenungan. Meme jadi alat epistemik, cara mereka memahami dunia. Dalam meme tentang Bahlil, misalnya, mereka sedang mencoba memetakan relasi antara kekuasaan dan rakyat, antara otoritas dan representasi.
Maka, daripada dianggap ancaman, meme seharusnya dilihat sebagai pintu komunikasi baru. Internet culture menciptakan ekosistem yang jauh berbeda dari era televisi dan koran. Di sinilah Cupin berhenti sejenak, menghela napas, dan menulis di catatan kecilnya: “Kalau zaman dulu kekuasaan punya podium, sekarang publik punya template.”
Pertanyaannya tinggal satu: apakah figur publik siap berdialog dengan bahasa baru ini?
Dari Meme ke Momentum Branding Bahlil
Di sinilah Cupin mulai bersemangat. Ia yakin, viralnya meme bukan akhir, tapi awal. Meme bisa jadi branding goldmine kalau diolah dengan cerdas. Dalam dunia Gen Z, reputasi nggak dibangun lewat kesempurnaan, tapi lewat otentisitas.
Cupin membayangkan skenario alternatif. Bagaimana kalau Bahlil justru ikut main di ruang itu? Misalnya, dia bikin video singkat di TikTok, reaksi santai terhadap meme-memenya sendiri sambil bilang, “Wah, kreatif banget kalian!” Bayangin efeknya, langsung viral dua kali lipat tapi kali ini dengan sentimen positif.
Sarah Banet-Weiser dalam Authentic: The Politics of Ambivalence in a Brand Culture bilang bahwa di era digital, otentisitas adalah mata uang paling mahal. Publik bisa mencium ketidaktulusan dari jauh. Gen Z, apalagi, detektornya tajam. Mereka cepat tahu mana yang genuine dan mana yang cuma pencitraan.
Jadi kalau Bahlil bisa menunjukkan self-awareness, bahwa dia bisa tertawa bersama publik dan tidak marah, itu bukan kelemahan. Itu kekuatan. Cupin menulis di jurnalnya: humor is new authority.
Dalam konteks branding, ini bukan hal baru. Alice Marwick dalam Status Update: Celebrity, Publicity, and Branding in the Social Media Age menjelaskan bahwa tokoh publik yang sukses di media sosial adalah mereka yang menampilkan “performed intimacy.” Artinya, mereka kelihatan dekat dan manusiawi, tapi tetap punya wibawa.
Cupin lalu memberi contoh nyata. Akun resmi Partai Gerindra pernah menunjukkan strategi brilian ini. Waktu ada tweet lucu yang nyamain Prabowo sama bayi di iklan “mybaby,” alih-alih marah, akun Gerindra justru ikut bercanda, “Kijang satu, monitor…” Netizen langsung meledak ketawa. Responsnya bukan cuma lucu, tapi juga menunjukkan bahwa mereka paham cara kerja internet.
Cupin mengetik cepat: “That’s how you win the timeline.” Dengan ikut main, mereka bukan kehilangan wibawa, tapi justru mendapat simpati. Mereka terlihat fun, modern, dan nggak kaku.
Kalau strategi semacam itu diterapkan oleh Bahlil, efeknya bisa luar biasa. Meme yang awalnya terlihat seperti ejekan bisa diubah jadi titik balik citra publik. Ia bisa membuka dialog santai dengan anak muda soal hilirisasi, investasi, atau ekonomi digital, tapi dikemas dengan gaya yang playful dan komunikatif.
Joshua Meyrowitz dalam No Sense of Place menjelaskan bahwa media elektronik menghapus batas antara panggung depan dan belakang. Publik sekarang pengin lihat sisi “backstage” dari pejabat, yang manusiawi, jujur, dan bahkan kadang kikuk. Meme, kata Cupin, adalah undangan halus ke panggung belakang itu.
Kalau Bahlil bisa menanggapi dengan santai, dia bukan cuma dapat poin di mata netizen, tapi juga membuka era baru komunikasi publik di Indonesia. Ia bisa menunjukkan bahwa pemimpin modern itu bukan yang jauh dan formal, tapi yang bisa connect tanpa kehilangan substansi.
Cupin menutup laptopnya sambil tersenyum. Dalam hati, dia tahu bahwa yang sedang terjadi ini lebih besar dari sekadar meme. Ini tentang cara baru rakyat bicara kepada kekuasaan. Tentang bagaimana humor bisa jadi jembatan antara istana dan warganet.
Di akhir catatannya, Cupin menulis pelan: “Mungkin Bahlil nggak sedang di-olok, tapi sedang diundang.”
Diundang untuk hadir di ruang percakapan digital yang lebih cair, lebih manusiawi, dan lebih Indonesia karena, di zaman sekarang, branding bukan soal siapa yang paling berkuasa, tapi siapa yang paling bisa tertawa. (A43)